
Agama menurut saya sejauh ini membuktikan mampu berbicara panjang lebar dan detail mengenai "dunia gaib" (surga, neraka, malaikat, jin, alam akhirat termasuk bidadari di dalamnya), ibadah ritual (shalat, puasa, zikir beserta ornamennya), teologi (sifat dan zat Tuhan), moralitas individual dan lain-lain, namun hampir-hampir tidak menyinggung aspek lingkungan hidup (ekologi). Padahal lingkungan adalah masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan kita.
Sebagai konsekuensi logis fungsi agama untuk manusia, agama selalu difungsikan untuk menopang segala upaya demi keberlangsungan hidup umat manusia. Perubahan iklim yang kini mengancam kehidupan merupakan ulah manusia, karenanya musti menjadi perhatian khusus teologi. Agama yang baik adalah agama yang menjaga dan melestarikan, bukan menghancurkan dan memusnahkan kemanusiaan. Demikian Hans Kung menegaskan. Karenanya, diperlukan rekayasa teologis untuk kepedulian lingkungan sebagai format agama di masa yang akan datang.
Sebaliknya, sebagaimana postulat Stephen Sulaiman Schwartz dalam The Two Face of Islam: Saudi Fundamentalism and Its Role Terrorism bahwa jika agama tidak memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, despotik, dan tak acuh terhadap kehidupan, tidak menutup kemungkinan akan lenyap ditelan sejarah manusia sebagaimana pernah dialami agama pagan. Tetapi, Schwartz hendak menegaskan bahwa secara normatif teologi Islam tidak demikian. Corak teologi yang hanya mengurus Tuhan an sich dan melupakan persoalan bumi tidak akan bertahan lama. Masa depan agama akan ditentukan sejauh mana ia bermanfaat untuk kehidupan manusia di bumi.
Karena itu, sudah seharusnya nalar bumi ditegakkan pada akar teologi. Penempatan manusia sebagai khalifah fil al ardhi dalam Islam sesungguhnya bukan berarti menegaskan perspektif human sentris dengan menempatkan bumi berada dalam kuasa manusia secara mutlak untuk bebas dikonversi dan dieksploitasi. Tetapi, sebagai wakil-Nya, manusia harus menjaga kelestarian alam. Keterciptaan manusia dari tanah memerankan bumi laiknya “ibuâ€yang melahirkan Adam hingga beranak-pinak. Sebagai “ibuâ€,ia harus dirawat dan dikasihi, bukan dieksploitasi dan dikonversi tanpa moral dan etika. Itulah tugas sejati kekhilafahan manusia atas bumi. Bumi dan seisinya bukan dzat mati dan tanpa spiritualitas.
Tuhan berkal-ikali menjelaskan bahwa bumi dan seisinya senantiasa sabbaha lillaahi maa fissamaawaati wal-ardhi memuji-Nya, siang dan malam. Islam berupaya memposisikan alam dan manusia saling tergantung satu sama lain. Sekalipun demikian, kesadaran bumi yang sebenarnya ada dalam tradisi ajaran Islam, kurang mendapatkan ruang di dalam ilmu-ilmu praksis seperti fiqh. Padahal, inilah inti kekuatan tradisi Islam, bukan pada aspek teologis. Karenanya, perlu juga merancang fiqh bumi sehingga orang yang merusak dapat digolongkan sebagai kafir ekologis. :)
Karena itu pula menegakkan nalar bumi bukan hanya kebutuhan, melainkan desakan untuk dimanifestasikan ke ranah yang lebih praksis, mengingat ancaman ekologis akibat global warming semakin mengkhawatirkan. Alam seperti halnya manusia memiliki carrying capacity-nya sendiri. Dalam teori Human Ecology, dikenal slogan ; "Pushing ecosystem to the limit is risky". Jika ekosistem didorong mendekati batas stability domain-nya dengan menggunakanecosystem services terlalu intensif, fluktuasi ekosistem alam dapat mendorong ekosistem ke domain yang lain dimana ecosystem services-nya berkurang.
Agama masih tetap memiliki ruang untuk menciptakan peradaban baru yang menyeimbangkan antara kemajuan teknologi-industri dengan kesadaran untuk menghargai alam. Dengan demikian, agama tidak melulu mengurus “langit†dan melupakan urusan bumi yang mengancam keberlangsungan umat manusia.
Akibat orang tidak mengindahkan lingkungan, malapetaka terjadi di mana-mana. Bukankah banjir dan sejumlah penyakit mematikan seperti demam berdarah juga terkait dengan masalah lingkungan? Dunia tidak hanya terjangkit krisis ekonomi, krisis moneter, krisis moral, krisis politik, krisis iptek, krisis budaya dan sebagainya tetapi juga krisis lingkungan.
Lihatlah juga pemandangan mengerikan dewasa ini: gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, polusi, badai, cuaca yang labil dan sebagainya hampir datang bertubi-tubi, silih berganti. Dunia seakan mengamuk dan destruktif sehingga menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia. Sudah tidak terhitung lagi berapa nyawa yang melayang, berapa jumlah anak yatim-piatu atau orang tua yang kehilangan buah hatinya yang masih tersisa, berapa jumlah harta benda dan properti lain yang amblas ditelan bencana.
So, mengapa umat beragama (termasuk umat Islam) tidak menganggap penting masalah lingkungan sebagaimana ibadah ritual-individual? Kenapa kita tidak tertarik melakukan penghijauan, kebersihan dan kegiatan lain yang bernuansa ramah lingkungan dan mencegah berbagai madhlarat (efek samping negatif) yang mungkin ditimbulkan dari alam yang tidak sehat?
Sebaliknya, kenapa kita lebih bergairah mengikuti aktivitas rohani: pengajian, zikir nasional, istighotsah dan semacamnya? Kenapa, meskipun bencana alam sudah terjadi sejak zaman purba bersamaan dengan kehidupan manusia, umat beragama tidak kunjung merenovasi wawasan keagamaan dan teologinya-sebuah wawasan keagamaan atau teologi yang berbasis ekologi (ekoteologi).
Tidak sedikit pula pada setiap terjadi bencana atau malapetaka, umat beragama dengan enteng tanpa beban dan perasaan dosa sedikit pun menganggap (menuduh?) sebagai takdir Tuhan, Sebagai cobaan atau azab dari Tuhan. Tuhan selalu "dikambinghitamkan" setiap terjadi malapetaka. Seperti kata Ebiet G. Ade, "tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat". Hampir tidak pernah, kita, menunjuk diri kita sendiri sebagai subjek yang bertanggung jawab terhadap malapetaka dan bencana tadi. Karena adanya keyakinan bahwa setiap malapetaka sebagai "siksa" atau "cobaan" dari Tuhan, maka setiap kali terjadi bencana yang dilakukan umat beragama adalah berdoa, mohon ampun, istighotsah, menggelar zikir nasional sambil menangis.
Saya tidak sedang meremehkan aktivitas ritual batin semacam ini akan tetapi terapi spiritual jenis ini di samping merendahkan (bahkan "mengolok-olok") martabat Tuhan karena menganggap-Nya sebagai zat yang "Maha Buas", dan hanya akan mereda dengan permohonan ampun. Cara demikian bagi saya hanya akan mengartikan kita hendak "cuci tangan"-melepaskan tanggung jawab-dari musibah kemanusiaan itu.
Padahal, jika kita menggunakan perspektif Schumacher dalam A Guide for the Perplexed, masalah krisis lingkungan ini sangat terkait dengan krisis kemanusiaan, dengan moralitas sosial serta krisis orientasi kita terhadap Tuhan. Mengikuti kerangka berpikir Schumacher ini, maka seharusnya manusia yang dipersalahkan dan bukannya Tuhan. Kitalah yang melakukan berbagai tindakan destruktif terhadap alam semesta.
Perusakan lingkungan, penebangan liar, eksploitasi properti alam secara besar-besaran dan segala tindakan merusak alam lain merupakan sumber malapetaka dan bencana tadi. Bukankah al-Quran sendiri juga telah mengingatkan bahwa "Kerusakan di darat dan laut adalah akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab"? Jika al-Quran sendiri menganggap manusia sebagai mastermind dari kerusakan lingkungan, lalu kenapa kita justru menyalahkan Tuhan? Bukankah, kita umat manusia-jika mengikuti alur cerita kitab-suci agama Semit-pada dasarnya "terbuang" dari surga juga akibat tidak mengindahkan ajaran fundamental Tuhan, dan melanggar kearifan ekologi dengan telah memakan dan merusak pohon kekekalan.. Wallau'alam... (mi)
Senarai Bacaan
Al Qurtuby, S., 2008. Agama dan Masalah Krisis Lingkungan
Chapman, A.R., 2007. Consumption, Population, & Sustainability; Perspective From Religion & Science
Indra H., 2002. Kesadaran Teologi Bumi.
Low, N., dan Brendan G., 2009. Justice, Society & Nature; An Exploration of Political Ecology
Marten, G., 2001. Human Ecology; Basic Concept for Sustainable Development
Schwartz, S.S., 2005. The Two Face of Islam: Saudi Fundamentalism and Its Role Terrorism
Tulisan ini juga pernah dimuat di : http://green.kompasiana.com/penghijauan/2010/08/10/ekoteologi-mendekati-tuhan-melalu-perspektif-ekologi-221069.html
Sumber gambar : Guillaume de Germain



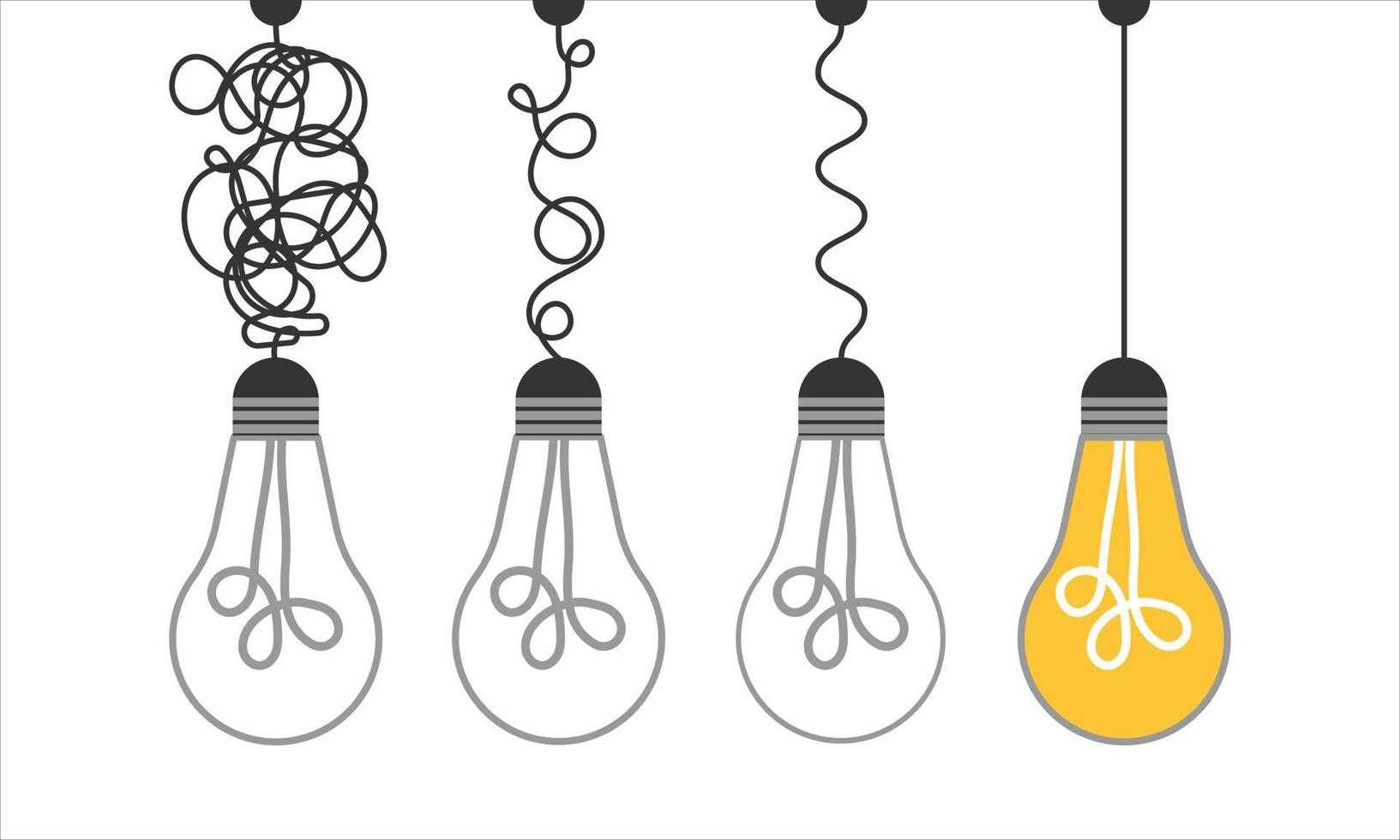






Itu karena umat manusia/beragama (termasuk sebagian umat islam) seolah mendikotomikan/membedakan, urusan dunia dan agama. Padahal agama hadir untuk petunjuk selamat akhirat dan dunia.
“Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,†mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikanâ€. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar†(QS al-Baqarah:11-12).
Tanggung jawab Dakwah untuk semua, dan disesuaikan, kamu muslimin harus mengilmui dari sisi keilmuanmya sendiri dan ilmi agama yang berkaitan dengan dunianya. Sehingga mampu mendakwahkan dengan ucapan dan Perbuatan. Di Lingkungannya. Sehingga agama dapat hadir disebelah aspek kehidupan. Termasuk ekologi.